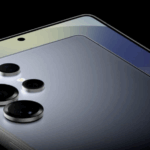Gelombang kecaman global kembali menghantam Israel setelah pemerintah negara tersebut mengesahkan serangkaian kebijakan baru yang dinilai kian mengokohkan cengkeraman pendudukan di Tepi Barat. Kebijakan itu dipandang bukan sekadar langkah administratif, melainkan manuver politik yang membuka jalan lebar bagi perluasan permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang telah lama berada di bawah bayang-bayang konflik.
Pada Senin (9/2/2026), delapan negara dengan mayoritas penduduk Muslim secara terbuka menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan tersebut. Melalui pernyataan bersama, para menteri luar negeri Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turki menegaskan sikap kolektif mereka. Mereka menyatakan bahwa mereka “mengutuk sekeras-kerasnya keputusan dan tindakan ilegal Israel yang bertujuan untuk memaksakan kedaulatan Israel yang melanggar hukum”.
Pernyataan yang dirilis oleh pemerintah Arab Saudi itu menekankan bahwa kebijakan Israel tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian langkah sistematis yang bertujuan mengubah lanskap hukum dan tata kelola administratif di Tepi Barat. Wilayah yang seharusnya berada di bawah rezim pendudukan sementara, kini dinilai tengah diarahkan menuju perubahan status secara sepihak.
Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai upaya “memperkuat aktivitas pemukiman dan memberlakukan realitas hukum dan administratif baru di Tepi Barat yang diduduki, sehingga mempercepat upaya aneksasi ilegal dan pengusiran rakyat Palestina”. Bagi banyak pihak, kebijakan ini ibarat paku yang semakin dalam ditancapkan ke peti mati harapan perdamaian yang adil.
Kecaman internasional ini mencuat sehari setelah pemerintah Israel menyetujui kebijakan baru yang diumumkan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Pertahanan Israel Katz pada Minggu sebelumnya. Dalam pernyataan bersama, kedua pejabat tersebut menegaskan bahwa salah satu inti kebijakan adalah memberikan izin bagi warga Yahudi Israel untuk membeli tanah di Tepi Barat, sebuah wilayah yang statusnya masih disengketakan di mata hukum internasional.
Tak berhenti di situ, aturan baru juga mencakup rencana pengalihan kewenangan perizinan pembangunan permukiman di sejumlah kota Palestina, termasuk Hebron. Kewenangan yang sebelumnya berada di tangan otoritas kotamadya Otoritas Palestina (PA) kini akan ditarik ke tangan pemerintah Israel. Artinya, keputusan strategis terkait pembangunan di kawasan sensitif akan dikendalikan langsung dari Tel Aviv, bukan lagi oleh otoritas lokal Palestina.
Bezalel Smotrich secara gamblang menyatakan bahwa kebijakan ini tidak semata-mata bersifat teknokratis. Ia mengakui adanya tujuan politik yang lebih dalam di balik kebijakan tersebut.
Ia mengatakan langkah tersebut bertujuan untuk “memperdalam akar kita di semua wilayah Tanah Israel dan mengubur gagasan negara Palestina”.
Pernyataan itu memperkuat kekhawatiran luas bahwa Israel tengah mendorong aneksasi de facto atas Tepi Barat. Banyak pengamat menilai, kebijakan tersebut bukan hanya mempersempit ruang hidup warga Palestina, tetapi juga menggerus fondasi solusi dua negara yang selama puluhan tahun dijadikan kerangka utama dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina.
Dari pihak Palestina, Kantor Kepresidenan di Ramallah—yang hanya memiliki kendali terbatas atas wilayah-wilayah yang terfragmentasi di Tepi Barat—ikut melontarkan kecaman keras. Dalam pernyataannya, kepresidenan Palestina menyebut kebijakan Israel bertujuan untuk “makin mengintensifkan upaya untuk mencaplok Tepi Barat yang diduduki”.
Momentum pengumuman kebijakan ini turut menjadi sorotan tajam. Langkah tersebut diumumkan hanya beberapa hari sebelum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan melakukan kunjungan ke Amerika Serikat. Dalam agenda itu, Netanyahu akan bertemu Presiden AS Donald Trump, yang secara resmi masih mempertahankan posisi Washington menentang aneksasi Israel atas Tepi Barat.
Namun, kebijakan terbaru Israel justru dipandang berjalan berlawanan dengan sikap komunitas internasional, termasuk Amerika Serikat. Selama ini, perubahan sepihak atas status wilayah pendudukan selalu menjadi garis merah dalam diplomasi global terkait konflik Timur Tengah.
Saat ini, lebih dari 500.000 warga Israel diketahui tinggal di permukiman dan pos-pos permukiman di Tepi Barat. Keberadaan permukiman tersebut secara luas dianggap melanggar hukum internasional. Di sisi lain, sekitar tiga juta warga Palestina hidup di wilayah yang sama di bawah berbagai lapisan kontrol militer dan administratif Israel, membentuk realitas kehidupan yang timpang dan sarat pembatasan.
Selain Tepi Barat, Yerusalem Timur juga menjadi bagian dari persoalan yang belum tuntas. Sekitar 200.000 warga Israel menetap di wilayah tersebut setelah dianeksasi Israel, meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menyatakan Yerusalem Timur sebagai bagian dari teritori Palestina yang diduduki.
Dengan kebijakan terbaru ini, banyak pihak menilai bahwa konflik Israel-Palestina kembali berada di persimpangan jalan. Alih-alih membuka pintu dialog, langkah Israel justru dinilai mempertebal tembok ketidakpercayaan dan menjauhkan peluang perdamaian yang berkelanjutan.