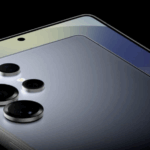Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap fakta mengkhawatirkan terkait paparan ideologi kekerasan ekstrem pada anak-anak di Indonesia. Berdasarkan pemantauan aparat, sedikitnya terdapat 70 anak yang terindikasi telah terpengaruh paham tersebut. Meski berasal dari latar belakang berbeda, anak-anak yang terpapar menunjukkan pola perilaku yang nyaris serupa, seolah bergerak dalam irama yang sama.
Juru Bicara Densus 88 Polri, Kombes Mayndra Eka, menjelaskan bahwa paparan ideologi kekerasan ekstrem tidak muncul secara tiba-tiba. Ada tanda-tanda awal yang bisa dikenali sejak dini. Ia memaparkan sedikitnya enam ciri yang kerap muncul pada anak yang mulai terpengaruh paham tersebut.
Salah satu indikasi paling awal adalah ketertarikan berlebihan terhadap simbol, nama, atau figur pelaku kekerasan. Ketertarikan itu biasanya diwujudkan melalui barang-barang pribadi, mulai dari coretan, aksesori, hingga unggahan digital.
“Ini bisa jadi menjadi tokoh idola atau sosok yang ingin diikuti perilakunya,” kata Mayndra dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (7/1/2025).
Selain itu, anak yang terpapar cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Jika sebelumnya aktif bergaul, mereka perlahan memilih menyendiri dan menghabiskan waktu berjam-jam di ruang digital. Dunia maya menjadi “ruang sunyi” yang justru dipenuhi konten keras, salah satunya melalui komunitas penyuka kekerasan seperti True Crime Community (TCC).
Perubahan perilaku juga tampak dari kecenderungan meniru tokoh atau idola yang dikagumi. Peniruan itu tidak hanya sebatas ucapan, tetapi merambah gaya berpakaian, unggahan media sosial, hingga penggunaan atribut tertentu.
“Suka menirukan tokoh atau idola. Nah ini sudah terbukti, kita memiliki insiden–pernah terjadi insiden di SMAN 72 dan ABH yang melakukan tindakan tersebut, dari replika senjatanya, dari postingannya, dari gaya berpakaiannya,” ucapnya.
Ciri lain yang tak kalah mengkhawatirkan adalah konsumsi konten kekerasan yang dinilai tidak wajar. Anak-anak ini kerap mengakses tayangan brutal secara berulang, seolah kekerasan menjadi tontonan biasa, bukan lagi sesuatu yang menimbulkan empati atau rasa ngeri.
“Konten yang diakses tidak normal, sehingga kalau orang normal melihat itu pasti tidak tega melihat kejadian-kejadian kekerasan yang sering diunggah di komunitas tersebut,” lanjut Mayndra.
Akibatnya, anak akan menunjukkan reaksi emosional berlebihan ketika ponsel atau perangkat digitalnya dilihat orang lain. Mereka kerap beralasan bahwa apa yang diakses merupakan ranah privasi, padahal di balik layar tersimpan konten yang sarat kekerasan.
Tanda terakhir yang dianggap paling berbahaya adalah kebiasaan membawa senjata replika atau benda tajam ke sekolah. Bagi Densus 88, perilaku ini bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan simbol inspirasi untuk melakukan kekerasan.
“Kadang dia bawa ke sekolah untuk dibuat inspirasi melakukan kekerasan,” imbuh Mayndra.
Komunitas TCC Tumbuh Sporadis
Dalam kesempatan yang sama, Mayndra juga menyoroti maraknya komunitas True Crime Community di berbagai platform media sosial. Komunitas ini dinilai berkembang pesat dan menjadi medium penyebaran ideologi ekstrem, terutama kepada anak-anak dan remaja.
Berbeda dengan organisasi terstruktur, komunitas TCC tidak memiliki pendiri tunggal atau institusi resmi. Ia tumbuh liar, mengikuti arus teknologi digital yang tanpa batas negara.
“Komunitas ini tidak didirikan oleh tokoh pendiri organisasi maupun institusi, tetapi dia tumbuh secara sporadis seiring dengan perkembangan media digital yang merupakan pertemuan antara minat seseorang terhadap kekerasan, sensasionalisme media, dan ruang digital yang transnasional,” terang Mayndra.
Dari pantauan global, Densus 88 mencatat bahwa berbagai insiden kekerasan massal terjadi hampir sepanjang tahun 2025. Polanya serupa, yakni terinspirasi dari konten dan interaksi di komunitas daring.
“Data global memperlihatkan, ini kami ambil beberapa contoh ya, dari Januari sampai dengan Desember (2025) hampir masif ya terjadi beberapa kekerasan,” ujarnya.
Ia menambahkan, anak-anak dalam komunitas tersebut saling memantik inspirasi. Salah satu contoh ekstrem terjadi di Rusia, ketika seorang pelaku kekerasan menuliskan frasa “Jakarta Bombing 2025” pada senjatanya, merujuk pada insiden pengeboman di SMAN 72 Jakarta.
“Di dalam gagang senjata, pelaku penusukan di Moscow Rusia ini, kita bisa lihat bahwa dia menuliskan ada ‘Jakarta Bombing’ ya di situ. Dituliskan bahwa ‘Jakarta Bombing 2025’,” ungkap Mayndra.
“(Foto itu) diambil oleh yang bersangkutan kemudian di-upload di dalam komunitas in. Nah, diduga ini terinspirasi adanya insiden bom SMAN 72 di Jakarta,” pungkasnya.
Paparan ini menjadi alarm keras bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat luas bahwa ideologi kekerasan ekstrem bisa menyusup secara perlahan, senyap, namun mematikan, terutama melalui ruang digital yang kini tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak.