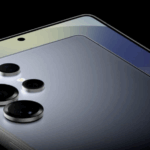Fenomena pernikahan anak kembali menjadi sorotan publik setelah viralnya video pernikahan remaja berusia sekolah di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). Peristiwa ini memicu respons dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang mendesak penegakan hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.
Kejadian tersebut menyangkut pasangan remaja: seorang siswi SMP berinisial SMY (15 tahun) dari Desa Sukaraja, Kecamatan Praya Timur, dan pelajar SMK berinisial SR (17 tahun) dari Desa Braim, Kecamatan Praya Tengah. Tayangan video adat nyongkolan, yang memperlihatkan prosesi pernikahan adat Sasak, memperlihatkan SMY berjalan ke pelaminan sambil menari, diiringi oleh dua perempuan dewasa yang mengusungnya. Aksi itu mengundang banyak respons dari warganet.
Salah satu komentar yang muncul dari akun Facebook @Dede Zahra Zahra menyatakan, “Org (orang) stres suruh nikah gimana ceritanya,” menggambarkan kegelisahan publik terhadap situasi tersebut.
Komisioner KPAI, Ai Rahmayanti, dengan tegas menyuarakan keprihatinannya terhadap praktik pernikahan anak yang dilakukan tanpa prosedur hukum resmi. Ia mengungkapkan bahwa kejadian semacam ini kerap tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga tanpa izin resmi berupa dispensasi kawin. Akibatnya, pernikahan berlangsung secara siri atau tidak tercatat secara hukum.
“Ini juga harus ada sanksi yang tegas kepada pihak-pihak yang terlibat di dalam perkawinan anak ini, karena menurut pengawasan kami di tahun lalu dan tidak menutup kemungkinan hari ini perkawinannya kan tidak dilakukan di KUA dan tidak melalui dispensasi kawin. Artinya ini menikah di bawah tangan atau siri, yang melakukan biasanya imam desa atau sebutan penghulunya, ini juga harus diberikan sanksi tegas,” kata Ai Rahmayanti kepada wartawan, Minggu (25/5/2025).
Ia juga menyinggung bahwa di kalangan masyarakat Suku Sasak, masih hidup kuat tradisi Merariq, sebuah adat kawin lari yang kerap disalahpahami. Sejatinya, sanksi dalam konteks adat itu ditujukan kepada orang tua, bukan kepada anak. Namun, dalam praktiknya, pemahaman itu seringkali terdistorsi.
“Beberapa tokoh adat sebetulnya menyampaikan sanksi itu untuk orang tua, bukan untuk anak, karena yang memiliki tanggung jawab adalah orang tua. Namun sebagian besar salah menafsirkan terkait nilai-nilai budaya, bahwa yang disanksi ketika sudah ada tradisi merariq, maka yang disanksi itu anaknya. Padahal secara nilai, secara adat yang harus disanksi itu orang tua,” ucapnya.
Ai menekankan pentingnya mencegah perkawinan dini dengan cara menggandeng pemuka adat dan tokoh agama. Mereka diharapkan bisa menjadi corong untuk menyampaikan nilai-nilai edukatif kepada masyarakat, terutama para orang tua.
“Maka ke depan pencegahan perkawinan anak ini perlu juga dilibatkan tokoh adat untuk menyampaikan kepada orang tua bahwa sesungguhnya yang perlu dikasih sanksi itu adalah orang tua.”
“Edukasi ke masyarakat ini harus dimasifkan lagi dengan melibatkan para tokoh agama dan tokoh adat. Kenapa? Karena masyarakat masih melakukan perkawinan anak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Joko Jumadi, memberikan tanggapan terhadap perilaku mempelai perempuan dalam video yang tersebar. Ia menyatakan belum dapat mengambil kesimpulan mengenai kondisi kejiwaan anak tersebut tanpa pemeriksaan profesional.
“Nanti. Kami belum bisa memastikan itu. Nanti pada proses pemeriksaan kepolisian. Kita tidak bisa menjustifikasi kenapa-kenapa, semua harus melalui pemeriksaan tenaga medis, dan itu akan kita lakukan,” jelasnya.
Kasus ini menjadi potret suram dari persoalan yang tak kunjung terselesaikan: pernikahan anak. Layaknya akar ilalang yang tumbuh liar di ladang hukum dan budaya, praktik ini tetap subur ketika edukasi minim dan penegakan aturan lemah. KPAI dan para pemangku kepentingan pun dituntut hadir sebagai mata air yang menyejukkan serta menata ulang bentang sosial demi masa depan anak-anak Indonesia.